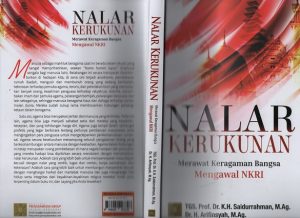
Salah satu buku karya Prof Dr Saidurrahman MAg. (foto/msj)
Oleh : TGS Prof Dr KH Saidurrahman MAg
Mungkin bagi sementara kita, telah secara keliru menyoal tentang tingginya perhatian Pemerintah dan sejumlah kalangan terhadap Pancasila sebagai ideologi Bangsa Indonesia pada benerapa waktu belakangan ini. Mulai dari Pendirian Badan Pembinaan Idrologi Pancasila (BPIP), diskursus panjang seputar RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP), hingga sekarang bergulirnya gagasan melahirkan RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP).
Dalam forum-forum tertentu misalnya, telah terdengar ungkapan-ungkapan yang bernada miring dan bahkan sinis seperti: “Padahal begitu banyak masalah lain di negeri ini, kemiskinan, penyakit menular, ketertinggalan—-tapi kenapa sih justeru Pancssila saja yang dibahas-bahas”. Ungkapan lain “Begitu banyakanya persoalan rakyat yang lebih mendesak seperti harga bahan pokok, ketersediaan lapangan kerja dan gagal panen, tapi mengapa Pemerintah justeru sibuk mengurusi ideologi, radikalisme dan seterusnya. Tentu saja masih terdapat sejumlah ungkapan yang senada atau bahkan yang lebih apatis yangvdapat didengarkan pada berbagai kesempatan.
Sepintas, tidak terlihat ada yang salah dari ungkapan-ungkapan bernada sinis-apatis di atas, bahkan lewat sudut pandang tertentu dapat dilihat sebagai sesuatu yang wajar dan masuk di akal. Namun, jika cara pandang ini didekati dari fakta bahwa demikian kuat serta pentingnya relasi antara ideologi suatu bangsa dengan bagaimana anak bangsa tersebut menghadapi dan menjalani kehidupan di tengah arus globalisme dan digitalisme, maka akan tampaklah dengan jelas mengapa fenomena-fenomena, persoalan-persoalan kehidupan berbangsa harus ditarik dan didukkukan terlebih dahulu via a vis dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi yang dianut.
Penting disadari bahwa, globalisme yang saat ini sedang dibonceng oleh digitalisme, telah berjalan sedemikian kencangnya. Bergerak halus bagaikan evolusi-substantif menembus dan menpis batas-batas, sekat-sekat hingga jadilah penghuni bumi seperti berada dalam satu kampung saja. Dalam situasi ini, budaya dan tradisi akan berevolusi, melebur dan akan mencari titik temu atau bahkan menyatu. Begitupun pola pikir, etika dan bahasa akan berasimililasi untuk menemukan persinggungan-persinggungan hingga mengarah kepada inklusivitas dan menyatu. Lebih jauh, agama dalam arti teologi dan spiritual secara perlahan akan mencari titik temu pada dimensi esoterisnya untuk kemudian dapat melebur dan menyatu.
Dapat dibayangkan, bagaimana rasanya jika suatu saat bumi ini benar-benar seperti yang digambarkan di atas, dimana setiap orang akan kehilangan identitas dirinya karena telah melebur dalam naungan globalisme dan universalisme. Hidup tanpa identitas pada satu sisi bisa saja dipandang menarik sebab memunngkinkan terbangunnya egalitarianisme yang seolah menjadi kata lain dari humanisme dan keadilan.
Akan tetapi, dalam banyak hal situasi ini justeru dipandang dapat memicu disharmoni, hegemoni bahkan eksploitasi. Disebut begitu, marena setiap kali satu gagasan penyatuan dimunculakn seperti universalisme, globalisme, humananisme, internasionalisme. Maka selalu saja tercipta pembelahan dunia, dimana sebagian menjadi subjek sedangkan yang lainnya malah menjadi objek. Dalam bahasa kamibdi Medan Sumatera Utara, selalu saja ada yang menjadi pemain dan ada yang justeru kena mainkan. Terhadap kondisi ini saya teringat pada ajaran sang guru nalar Jean-Jacques Rousseau (1712–78) yang mengatakan bahwa pada awalnya manusia berkehendsk untuk membangun komitmen bersatu, bekerjasama saling bantu untuk secara bersama-sama dapat bertahan dan memenuhi kebutuhan hidupnya.
Untuk tujuan itulah dibangun konsep-konsep yang dapat mengikat dan melebur keinginan serta kebutuhan bersama dalam satu rumusan seperti humanisme, universalisme dan seterusnya itu. Namun, situasi ini tidak berjalan mulus, di tengah-tengah upaya bersatu tersebut, muncullah persaingan, pembatasan kebebasan dan pada akhirmya melahirkan percekcokan dan bahkan memunculkan cara pandang dimana seseorang menadang selainnya sebagai lawan atau mangsanya.
Dalam situasi demikian ini, maka mesti ada tempat kembali, dimana setiap orang memiliki identitas khas disertai hak-hak yang diperoleh secara alamiah atau kodrati. Rousseau menyebut dengan “back to nature”— kembali kepada eksistensi alamiah. Hanya saja, istilah kembali kepada situasi alamiah ini telah me jadi rancu terutama saat sekarang ini, karena yang alamiah telah berobah secara tidak evolutif dan mandiri semata, melainkan telah dipicu bahkan dalam situasi tertentu dipaksa oleh revolusi nalar, industri hingga teknologi dan digitalisme.
Karenanya, tempat kembali yang paling rasional adalah kembali ke Bangsa masing-masing, kembali kepada ideologi masing-masing. Ideologi Bangsa yang dapat mewadahi, memperjuangkan dan mempertahankan identitas beserta hak-hak dasar alamiah setiap anak bangsa. Bangsa atau ideologi tidak boleh melebur, meski penduduk dunia perlu bekerjasama. Pada Bangsa, ada tanah, air, tumpah darah, jiwa dan raga yang padanya terinternalisasi identitas khas yang akan abadi dan mengikat anak bangsa dengan bangsanya atau dengan ideologinya.
Terhadap hal ini, menarik sekali penjelasan Prof. KH. Yudian Wahyudi (Founder Thariqah Sunanu al-Anbiya, Kepala BPIPl — bahwa secara teologis terdapat dua jenis ruga atau “al-jannah”: surga (al-jannah) di akhirat yang ghaib dan tidak butuh untuk terlalu dibahas dan surga (al-jannah) di dunia yang justeru lebih mendesak untuk dibahas. Surga (al-jannah) di dunia dapat dimaknai sebagai wadah yang dapat menyediakan, memenuhi, memelihara dan mempertahankan identitas suatu kelompok manusia dilambangkan dengan pohon (al-syajarah) yang dapat bermakna suatu Bangsa yang memiliki ideologi.
Suatu Bangsa dengan ideologi yang kuat dan abadi akan mampu menjaga fithrah dan identitas penganutnya secara abadi. Mampu mewadahi cita-cita, ide, gagasan, kreasi dan inovasi penganutnya tanpa harus kehilangan identitasnya yang sejati. Ideologi dapat mewadahi dan memfasilitasi penganutnya agar dapat berdiri dan duduk sejajar dengan bangsa lain atau penganut ideologi lain tanpa harus terlebur ataupun tereduksi secara eksistensial.
Ideologi Bangsa dengan demikian akan menjadi benteng pertahanan terakhir bagi anak bangsa untuk mempertahankan identitas serta hak-hak azasi yang dimilikinya secara alami di saat berbagai dimensi kehidupan dan peradaban seakan sedang dipaksa untuk melebur dsn menyatu, bahkan hingga terancam akan kehilangan identitas dan boleh jadi dapat me jadi kehilangan eksistensi.
Jika alur pikir ini dspat diterima, maka memberikan perhatian yang besar serta serius terhadap pengkajian, penguatan, pembinaan, sosialisasi dan pembumian ideologi Pancasila terlebih di tengah-tengah tantangan universisme, globalisme, digitalisme menjadi sangat penting, fundamental, mendesak dan strategis untuk terus dijaga dan ditingkatkan. Dengan begitu gagasan untum melakukan percepatan penyusunan, penetapan dan pengesahan RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) menjadi sangat penting dan mendesak untuk terus didorong dan serta diberi dukungan.**
** Penulis adalah Rektor UIN Sumatera Utara Medan, Wakil Rais Syuriah PW NU Sumatera Utara **
- Klinik Pratama Rutan Kelas I Medan Bekali CPNS Tenaga Kesehatan, Kanwil Ditjenpas Sumut – Juli 9, 2025
- Rapat Bersama Badan Anggaran DPR RI, Sekjen Kementerian ATR/BPN Optimis Ada Peningkatan PNBP pada 2026 – Juli 9, 2025
- Wali Kota Binjai Terima Kunjungan Kerja Anggota DPRD Sumut, Bahas Sejumlah Isu Strategis Daerah – Juli 8, 2025










